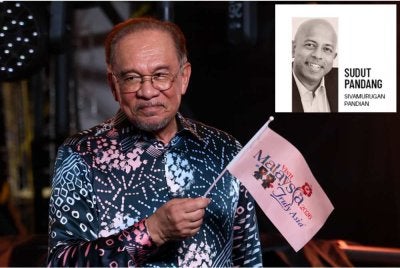Media sosial sebagai Parlimen tidak rasmi demokrasi Malaysia

DALAM landskap politik Malaysia hari ini, wacana awam tidak lagi bermula di Parlimen, sebaliknya tercetus di media sosial.
Sebelum sesuatu dasar dibahaskan secara menyeluruh di Dewan Rakyat, dasar tersebut sudah pun ditafsir, dinilai dan diperdebatkan di Twitter (X), TikTok dan Facebook.
Klip video berdurasi singkat sering membentuk persepsi awam dengan lebih pantas berbanding perbahasan rasmi yang panjang dan berlapik. Fenomena ini mencerminkan satu realiti baharu demokrasi, iaitu media sosial kini berfungsi sebagai “Parlimen tidak rasmi” rakyat.
Perubahan ini membawa sisi positif apabila media sosial meluaskan akses kepada wacana politik. Rakyat biasa kini boleh menyuarakan pandangan, mengkritik dasar dan memantau pemimpin tanpa bergantung sepenuhnya kepada institusi tradisional.
Dalam kerangka teori ruang awam yang diperkenalkan oleh Jürgen Habermas, penglibatan rakyat dalam perbincangan awam merupakan asas kepada demokrasi yang hidup.
Namun persoalan penting yang timbul ialah sama ada ruang awam digital hari ini benar-benar menggalakkan perbincangan yang rasional dan berasaskan maklumat.
Berbeza dengan Parlimen yang terikat kepada peraturan, prosedur dan rekod rasmi, media sosial digerakkan oleh algoritma. Algoritma ini tidak menilai hujah berdasarkan ketepatan atau kualiti, sebaliknya berdasarkan tahap keterlibatan pengguna. Kandungan yang mencetuskan emosi seperti kemarahan, ketakutan atau keterujaan cenderung untuk disebarkan dengan lebih meluas berbanding analisis yang berhati-hati dan bernuansa.
Kajian oleh Massachusetts Institute of Technology (MIT) yang diterbitkan dalam jurnal sains menganalisis lebih 126,000 rantaian penyebaran maklumat di media sosial sepanjang hampir sedekad. Dapatan kajian tersebut menunjukkan bahawa kandungan palsu membentuk majoriti aliran penyebaran berbanding kandungan benar, termasuk dalam isu politik. Corak ini mencerminkan kecenderungan struktur dalam ekosistem media sosial yang memberi kelebihan kepada maklumat sensasi dan emosional berbanding fakta yang memerlukan konteks serta penjelasan mendalam.
Realiti ini membantu menjelaskan mengapa wacana politik dalam ruang digital sering berkembang secara reaktif. Apabila maklumat palsu dan separa benar lebih dominan dalam arus perbincangan, perbahasan awam mudah terperangkap dalam emosi dan persepsi, bukannya analisis dasar yang berasaskan bukti. Politik lalu beralih daripada ruang pertimbangan rasional kepada medan respons segera.
Implikasinya terhadap pemimpin politik juga signifikan. Tekanan untuk mengurus persepsi di media sosial mendorong sesetengah pihak memberi keutamaan kepada simbol dan kenyataan yang mudah tular, berbanding perancangan dasar yang rapi. Tadbir urus berisiko menjadi bersifat persembahan, bukan penyelesaian.
Dalam masa yang sama, kefahaman politik rakyat turut terkesan. Isu dasar yang kompleks seperti pembaharuan fiskal, subsidi bersasar atau reformasi institusi memerlukan masa serta kesabaran intelektual. Namun apabila isu-isu ini dipadatkan menjadi slogan atau potongan video pendek, nuansa dan konteks sering terkorban. Politik lalu direduksikan kepada dikotomi mudah: betul atau salah, pro atau anti.
Ahli falsafah politik, Hannah Arendt, pernah mengingatkan bahawa bahaya besar dalam politik moden ialah thoughtlessness, iaitu tindakan tanpa refleksi mendalam. Dalam konteks ini, media sosial berpotensi mempercepatkan budaya reaksi segera, di mana pendapat dibentuk tanpa penilaian kritis yang mencukupi.
Satu lagi implikasi penting ialah soal kebertanggungjawaban. Parlimen menyediakan mekanisme semak dan imbang melalui perbahasan berstruktur, jawatankuasa serta rekod rasmi. Media sosial pula beroperasi dalam kitaran perhatian yang singkat. Kontroversi hari ini mudah tenggelam keesokan hari, digantikan dengan isu baharu. Keadaan ini berisiko melemahkan tekanan awam yang berterusan terhadap pelaksanaan dasar dan janji politik.
Ini tidak bermaksud media sosial harus ditolak. Ia kini merupakan sebahagian yang tidak terpisahkan daripada demokrasi moden. Namun cabarannya ialah bagaimana platform ini digunakan secara bertanggungjawab.
Bagi pemimpin, hal ini bermakna menolak godaan untuk mentadbir berdasarkan algoritma semata-mata. Seperti yang ditegaskan oleh Max Weber, politik yang matang menuntut etika tanggungjawab, bukan sekadar niat atau populariti jangka pendek. Tadbir urus yang baik lazimnya bersifat teknikal, perlahan dan tidak sensasi.
Bagi rakyat pula, demokrasi menuntut lebih daripada sekadar reaksi emosi. Ia memerlukan kesediaan untuk membaca, menilai sumber dan memahami kerumitan dasar awam. Demokrasi bukan hiburan, sebaliknya amanah kolektif.
Akhirnya, Parlimen harus kekal sebagai institusi utama perbahasan dasar yang serius, manakala media sosial wajar berfungsi sebagai ruang penglibatan, bukan sebagai pengganti. Kesihatan demokrasi tidak diukur melalui sekuat mana ia bersuara, tetapi sejauh mana ia berfikir, menilai dan mendengar dengan teliti.
MUHAMMAD MUNZIR BIN MOHAMMAD NASIR
Pengerusi Kelab Mahasiswa Penyokong Pas Nasional
Muat turun aplikasi Sinar Harian. Klik di sini!